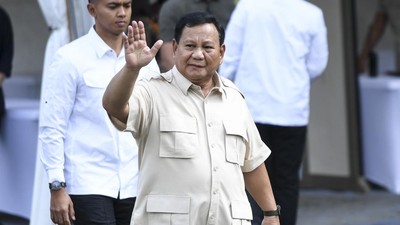Dilema ‘Gemuk’ Honorer Daerah: Desentralisasi vs Beban Keuangan

Jakarta – Carut marut honorer di Indonesia tampaknya belum bakal menemukan solusi konkret dalam waktu dekat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sejatinya tengah menata tenaga honorer di Indonesia.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas membuka pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) per 1 Oktober 2024, di mana 100 persen kuotanya untuk honorer.
“Seleksi PPPK 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah,” kata Anas dalam keterangan resmi, Rabu (2/10).
Namun, ia menyebut pemerintah daerah (pemda) justru tak memaksimalkan pembukaan 1,7 formasi PPPK di 2024. Anas mencatat kuota tersebut cuma terserap 1,2 juta formasi, di mana sejumlah pemda ada yang tak mengusulkan karena terbentur masalah anggaran.
Menpan RB Anas juga punya kekhawatiran lain. Ia was-was para kepala daerah dan anggota DPRD yang baru mengangkat honorer titipan usai Pilkada 2024.
“Ada masalah baru, jangan-jangan habis Pilkada (2024) naik lagi honorer ini. Betul ndak? Habis pilkada ini, pejabat baru, pejabat politik baru nambah. Maka konsistensi (penataan honorer) menjadi penting, kita kunci di rancangan peraturan pemerintah (rpp),” ucap Anas dalam SAKIP Award 2024.
“Kita kunci di situ (RPP Manajemen ASN). Sedang kita siapkan bagaimana bupati-bupati yang baru terpilih sama pimpinan dewan yang baru terpilih, ini biasanya mengangkat honorer untuk kepentingan beliau. Kita atur ini, tapi sepanjang jabatan itu yang terbatas, apakah 2 orang, 3 orang (honorer) nanti akan ada aturannya,” tuturnya.
Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menegaskan kekhawatiran Menpan RB Anas valid. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah membuat solusi yang jelas.
Achmad menilai negara harus mengatur batasan pengangkatan honorer. Ia menyarankan pemerintah membatasi jumlah honorer yang bisa diangkat pejabat baru berdasarkan kebutuhan nyata, bukan demi kepentingan politik semata.
“Mungkin ada pengecualian bagi daerah yang benar-benar kekurangan tenaga, tetapi pengangkatan honorer sebaiknya lebih berbasis pada analisis kebutuhan tenaga kerja daripada politik,” katanya.
“Secara ideal, jika formasi PPPK dan ASN sudah mencukupi, pengangkatan honorer baru seharusnya dibatasi secara ketat. Bahkan, tidak diizinkan sama sekali,” saran Achmad.
Ia menyoroti keberadaan tenaga honorer yang jumlahnya terus bertambah. Parahnya, pengangkatan dilakukan tanpa mekanisme seleksi yang ketat sehingga anggaran pemda bengkak.
Achmad mencatat rata-rata belanja pegawai di sejumlah pemda sudah melampaui batas ideal, yakni lebih dari 30 persen total anggaran. Bahkan, proporsi belanja pegawai di beberapa daerah bisa mencapai 40 persen-50 persen.
“Penting untuk dipahami bahwa anggaran pemda yang terlalu terkuras untuk membayar gaji pegawai, termasuk tenaga honorer, akan menyebabkan stagnasi pada sektor-sektor pembangunan yang krusial, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” wanti-wanti Achmad.
“Kemampuan anggaran pemda juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menambah pegawai. Setiap pemda memiliki kapasitas anggaran yang berbeda, tergantung pada penerimaan daerahnya. Jika anggaran sudah terbatas, memaksa menambah tenaga honorer hanya akan menambah beban keuangan tanpa meningkatkan kinerja secara signifikan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Achmad menekankan pentingnya intervensi dari pemerintah pusat. Ia menekankan negara sebaiknya menetapkan sanksi berat bagi pejabat daerah yang mengangkat honorer secara sembarangan. Ia menyebut sanksi ini bisa berbentuk administratif, seperti teguran. Achmad juga menyarankan hukuman yang lebih tegas berupa pemotongan insentif atau anggaran daerah yang dikelola pejabat tersebut.
“Jika terjadi pelanggaran serius, mekanisme penegakan hukum atau pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa diterapkan untuk mencegah praktik titipan honorer yang membebani keuangan negara,” tandasnya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai pemerintah pusat tidak bisa menggeneralisasi fenomena honorer di daerah. Apalagi, sampai melakukan intervensi berlebihan yang tak sesuai.
Ia menegaskan kebutuhan tenaga honorer di setiap daerah berbeda. Faisal juga menekankan tidak bisa negara menghapus tenaga kerja honorer secara total.
“Kalau mau semuanya langsung diatur, itu tidak sejalan dengan semangat desentralisasi. Jadi, pusat itu memang perlu melihat satu per satu, tidak menggeneralisasi. Misal, tidak boleh ada pengangkatan atau sebaliknya, ini bisa jadi salah kaprah karena satu sama lain (daerah) karakteristiknya berbeda,” jelas Faisal.
“Tapi memang dari pusat perlu mempertimbangkan, bukan hanya dari melihat besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk honorer. Kalau besar, tapi karena kebutuhannya begitu, ya tidak apa-apa,” sambungnya.
Ia menyebut negara seharusnya mengantisipasi peningkatan anggaran pemda untuk gaji honorer yang tidak sesuai produktivitas kerjanya. Apalagi, honorer yang diangkat hanya karena kepentingan politis pejabat daerah.
Di lain sisi, Faisal menyarankan pengangkatan honorer untuk pelayanan dasar di daerah jangan malah dikurangi atau dibatasi. Ia mencontohkan bagaimana sejumlah daerah masih kewalahan untuk melayani sektor pendidikan hingga kesehatan.
“Sekarang banyak pelayanan dasar yang tidak bisa terpenuhi dengan baik di daerah yang justru masih kekurangan tenaga. Karena keterbatasan anggaran juga tidak bisa semuanya di-ASN-kan. Jadi, justru gap antara kemampuan anggaran dengan kebutuhan tenaga pelayanan ini yang dijembatani dengan honorer,” tuturnya.
“Apalagi kalau kita lihat sekarang proporsi ASN pusat dan daerah itu lebih banyak di pusat secara agregat. Jadi, kita tidak bisa menyatakan di daerah itu kebanyakan staf (honorer). Ini juga bergantung pada kebutuhan,” imbuh Faisal.